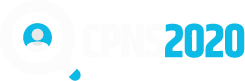Ribuan CPNS Mengundurkan Diri: Yang Belum Diketahui oleh Publik
 Ilustrasi CPNS. Gaji CPNS 2025. Berapa gaji CPNS 2025. Gaji CPNS 2025 sesuai golongan.
Ilustrasi CPNS. Gaji CPNS 2025. Berapa gaji CPNS 2025. Gaji CPNS 2025 sesuai golongan.DI MEDIA sosial, masih banyak netizen yang kerap menghakimi para peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus dan memilih mengundurkan diri.
Komentarnya beragam, mulai dari dianggap tidak bersyukur di saat banyak orang butuh pekerjaan, dinilai tidak berkomitmen karena seharusnya mengetahui dari awal bahwa ASN siap ditempatkan dimana saja dan penghasilannya tidak seberapa, serta dipandang tidak memahami nilai “pengabdian” menjadi seorang ASN.
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan ASN, kebijakan instansi mengenai pemilihan lokasi formasi atau unit kerja terbagi menjadi dua.
Pertama, sistem pengelompokkan formasi. Misalnya, ambil contoh dari instansi Bawaslu yang masuk kategori lima besar peserta paling banyak mundur.
Tersedia formasi analis hukum yang tersebar di seluruh provinsi. Kemudian, Bawaslu melakukan pengelompokkan formasi dalam sistem seleksi, sehingga pelamar hanya bisa memilih jabatan analis hukum, tanpa bisa memilih lokasi formasi.
Kedua adalah tidak ada pengelompokkan formasi (mirip seperti sistem zonasi), sehingga pelamar bisa memilih jabatan analis hukum di unit kerja secara spesifik, misalnya, analis hukum Provinsi Jawa Timur.
Artinya, dari dua pilihan kondisi ini, ada tipe pelamar yang dari awal sudah siap ditempatkan di mana saja dan ada pelamar yang mengikuti seleksi CPNS dengan niat bekerja di daerah domisili. Tentunya hal ini adalah hak masing-masing dari setiap individu.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala BKN dalam RDP dengan Komisi II DPR RI (22/4/2025), faktanya para peserta CPNS yang mundur didominasi oleh peserta yang lulus karena hasil kebijakan optimalisasi.
Baca juga: Optimalisasi Formasi CPNS: Efisien secara Angka, Tak Manusiawi secara Makna
Bagaimana sistem ini bekerja?
Secara singkat, mekanisme optimalisasi mengolah kembali peserta yang sebelumnya tidak lulus (dengan kategori nilai tertinggi setelah peserta yang lulus pemeringkatan), kemudian menempatkannya ke unit kerja lain yang belum terisi ketersediaan formasinya (dengan syarat jabatan yang dilamar sama).
Permasalahannya, mayoritas unit kerja yang tidak terisi ketersediaan formasinya adalah daerah-daerah 3T. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana kondisi kesenjangan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang masih terjadi antardaerah.
Artinya, mayoritas peserta yang mundur bukan tidak bersyukur atau tidak berkomitmen dengan pilihan.
Namun, mereka yang akhirnya tidak bersedia mengambil kesempatan kelulusan hasil optimalisasi adalah kategori peserta yang sejak awal memang tidak ingin bekerja jauh dari domisili atau daerah sekitarnya.
Lain cerita jika kasus peserta yang mundur bukan merupakan hasil optimalisasi atau mereka yang sejak awal mengetahui instansi yang dilamar tidak merinci unit kerja penempatan (sistem pengelompokkan).
Klausul pernyataan kesiapan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI baru bisa kita perdebatkan untuk kasus-kasus seperti ini.
Bekerja jauh dari domisili membutuhkan kesiapan mental yang kuat dan persiapan seluruh aspek kehidupan yang matang.
Kondisi demografis yang beragam dari setiap peserta seperti kondisi kesehatan orangtua yang ditinggalkan dan jauh dari keluarga, biaya hidup selama masa perantauan dan pengeluaran tiket pulang-pergi yang tidak seimbang antara penghasilan yang didapatkan seharusnya membuat publik tidak mudah menghakimi pelamar yang mundur dengan alasan domisili yang jauh dan penghasilan tidak sesuai ekpektasi.
Narasi pengabdian sebagai ASN juga terkadang mengaburkan persoalan sistemik sesungguhnya.
Baca juga: Alasan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Kecil hingga Penempatan Jauh
Dunia telah berubah dengan sangat cepat. Paradigma pola dan ekpektasi kerja telah bergeser. Tujuan bekerja saat ini tidak hanya sekadar mencari penghasilan, namun lebih luas daripada itu.
Apalagi, saat ini lapangan kerja banyak didominasi generasi muda. Generasi yang tumbuh dengan kesadaran pentingnya kesehatan mental dan menerapkan keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Aspek kesejahteraan psikologis, kualitas hubungan sosial pegawai, kesempatan untuk melakukan aktualisasi diri mesti dipertimbangkan secara serius oleh instansi pemerintah agar relevan dengan tantangan zaman.
Jangan lagi membungkus ketidakcakapan menyediakan ekosistem kerja yang berkualitas dan memenuhi kesejahteraan pegawai dengan narasi pengabdian.
Penguatan kebijakan mengatasi mundurnya CPNS
Kekosongan formasi lowongan jabatan menimbulkan kerugian, baik secara finansial dan kinerja lembaga. Proses seleksi yang panjang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, serta butuh waktu lama untuk bisa mengisi formasi tersebut.
Setidaknya ada empat kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik yang sifatnya preventif dan kuratif.
Pertama, penetapan formasi kebutuhan khusus putra/putri papua dan putra/putri daerah tertinggal.
Kedua, penyesuaian nilai ambang batas (passing grade) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi peserta dengan formasi kebutuhan khusus.
Ketiga, sistem optimalisasi sebetulnya adalah intervensi kebijakan yang mampu mengurangi kekosongan formasi. Hal ini terbukti sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKN bahwa kebijakan optimalisasi berhasil mengisi 88 persen formasi yang tidak terisi.
Keempat, pemberian sanksi bagi peserta yang mundur. Hal ini tertuang dalam Permenpan Nomor 6 Tahun 2024, bahwa peserta yang lulus tahap akhir seleksi kemudian mengundurkan diri dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
Fenomena mundurnya CPNS yang selalu berlangsung setiap periode seleksi tidak dapat dipandang secara administratif saja.
Persoalan ini penting karena menyangkut nasib para pencari kerja yang ingin meningkatkan taraf hidup dan pentingnya pemerataan birokrasi yang berkualitas di seluruh Indonesia.
Maka dari itu, evaluasi berkelanjutan dengan penguatan kebijakan yang sudah ada harus dilakukan.
Baca juga: Tukin, Sertifikasi, dan Dosen Swasta
Kuota formasi khusus perlu ditingkatkan untuk menyerap banyak tenaga kerja lokal, komposisi formasi khusus pada daerah-daerah tertinggal idealnya melebihi kuota formasi umum.
Nilai ambang batas SKD bagi formasi khusus juga perlu dianalisis kembali pelaksanaannya dengan mempertimbangkan statistik perolehan nilai yang didapatkan peserta seleksi pada beberapa tahun sebelumnya.
Sehingga nilai ambang batas yang diterapkan bisa menyesuaikan kondisi kesenjangan pendidikan dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat daerah tertinggal.
Sanksi blacklist tidak boleh mengikuti dua kali periode seleksi sepertinya belum menyelesaikan akar permasalahan.
Di luar dari empat kebijakan tersebut, pada akhir periode pemerintahan Jokowi sempat bergulir wacana pengusulan pemberian insentif tambahan bagi ASN yang ditempatkan di daerah tertinggal melalui Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN yang baru.
Insentif tambahan tersebut berupa pemberian ketentuan cuti tambahan, tunjangan khusus dan percepatan karier.
Namun, kebijakan yang sangat solutif dalam mengatasi permasalahan banyaknya CPNS yang mundur dan pemerataan ASN di daerah tertinggal tersebut hingga kini belum terealisasi.
Penting untuk kembali mengawal dan mewujudkan kebijakan insentif tambahan tersebut, karena kebijakan inilah yang paling menyentuh akar permasalahan bagi kesenjangan ASN di daerah-daerah tertinggal.
Sebab, tidak ada perantau yang ingin pulang ke kampung halaman dengan tangan kosong.